Peningkatan Partisipasi Perempuan Indonesia Pasca Pemilu 2009
-
Oleh: Hermina Wulohering, 22 Juni 2012
Pemilihan umum 2009 merupakan pemilu ketiga di Indonesia setelah reformasi bergulir, dan berkembang banyak wacana seputar pelaksanaannya. Pembicaraan, perdebatan dan diskusi banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang mengupas masalah-masalah pemilu, partai politik, electoral threshold dan yang tidak ketinggalan juga partisipasi politik perempuan dalam kehidupan berbangsa yang dalam hal ini dimanifestasikan melalui lembaga-lembaga politik. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia politik secara khusus dalam parlemen semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Demokratisasi politik di Indonesia sejak era reformasi telah memberikan peluang yang besar bagi perempuan untuk menduduki parlemen dan terjun ke dunia politik praktis. Ini berarti ada peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia setelah reformasi walaupun belum memenuhi kuota 30%. Perempuan semakin dekat dengan dunia politik, karena di dalam demokrasi perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik praktis dengan berpartisipasi dalam parlemen dan berkiprah menduduki jabatan-jabatan politik yang startegis serta berperan dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dengan proses yang demokratis.
1. Sejarah Partisipasi Perempuan Indonesia di Parlemen
Pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat di antaranya dari organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sangat demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.[1] Berbeda dengan periode Orde Lama (Era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.
Berdasarkan kajian dan pengamatan para analis politik dinyatakan bahwa pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru lebih sebagai sebuah pemilu yang memenuhi prosedur demokrasi, tidak secara substantif. Pemilu pada masa ini lebih sebagai sebuah rutinitas bagi sebuah negara demokratis, sehingga terkesan ada rotasi kekuasaan sebagai sebuah prasyarat demokrasi.[2] Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik akibat tarik menarik antarkekuatan partai politik dengan kekuatan lain yang memiliki peran kuat yakni militer, yang memiliki hubungan khusus dengan partai Golongan Karya (Golkar). Pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu. Pemilu 1999 menghasilkan 44 orang yang duduk di DPR atau sekitar 8,9%.[3]
Kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 2004 terbuka lebar dengan dicantumkannya kuota 30 persen sebagai nominasi calon legislatif dalam undang-undang pemilihan umum. Hal ini merupakan terobosan positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya diparlemen. Hal lain yang turut memberi warna pada pemilu kali ini adalah adanya ketentuan kuota minimal sebesar 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Perubahan ini tentu saja akan membawa implikasi politik yang cukup menyegarkan bagi kehidupan politik di masa mendatang. Bagaimanapun, selama ini kehidupan politik di Indonesia memang banyak didominasi oleh mainstream ideologi patriarkat. Hasil pemilu tahun 2004 menempatkan 65 orang (11,82%) perempuan di lembaga DPR, hanya meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.[4] Pencantuman kuota 30% bagi perempuan yang untuk pertama kalinya ini belum begitu terasa efisiensi dari penerapannya. Di satu sisi, ternyata tidak cukup untuk mewujudkan peningkatan partisipasi politik perempuan karena hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen, mengingat pencantuman kuota 30% pada pemilu 2004 hanya sekedar syarat yang tekesan ’basa-basi’ untuk menyenangkan kaum perempuan karena pada akhirnya laki-laki yang akan masuk ke parlemen. Banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, di samping calon legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut bawah juga mereka bukanlah pengurus ’teras’ partai. Mereka menjadi calon hanya sekedar untuk melengkapi kuota calon perempuan 30 persen. Sementara hasil Pemilu Legislatif 2009 menunjukkan pencapaian yang besar jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, meskipun belum memnuhikuota 30%. Hasil pemilu anggota legislatif perempuan adalah sebesar 17,49%.[5] Peningkatan yang signifikan ini adalah bagian dari keberhasilan atas upaya yang terus mendorong dan tetap mempertahankan penerapan kebijakan afirmatif dengan kuota 30% keterwakilan perempuan. Secara sadar dan rasional tetap mempertahankan dan melanjutkan kebijakan afirmatif ini dengan tetap memuat kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, maupun paket Undang-Undang politik. Di lembaga legislatif, keterwakilan politik perempuan Indonesia dalam parlemen berada pada peringkat ke-89 dari 189 negara.[6]
2. Affirmative Action dan Peningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi begitu penting sebagai bentuk pemberian keadilan terhadap perempuan atas hak politiknya. Salah satu cara yang berperan dalam peningkatan persentase partisipasi perempuan Indonesia adalah dengan kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak politik perempuan. Belajar dari negara-negara di dunia yang tingkat keterwakilan perempuannya baik, maka upaya affirmative action atas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi penting. Affirmative action dalam bentuk kuota dan zipper system menjadi kunci keberhasilan masuknya perempuan di dalam lembaga legislatif. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindak afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 telah mengakomodir affirmative action dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan hanya pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan zipper system di dalamnya. Tindak afirmasi dalam Pemilu 2004 dinilai banyak pihak memiliki kelemahan, karena tidak ada jaminan perempuan diletakkan dalam nomor urut kecil atau nomor urut jadi, sehingga pada akhirnya jumlah perempuan hanya 11,09% saja di antara 550 anggota DPR. Hal inilah yang menjadi pembelajaran penting terhadap Indonesia untuk meningkatkan angka representasi perempuan di dalam parlemen pada Pemilu 2009.
Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas adalah sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat guna menghasilkan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat idealnya diisi oleh mereka yang mewakili rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya baik di tingkat nasional ataupun daerah.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan Indonesia adalah sebesar 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk.[7] Artinya, kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama. Kondisi ini tentu saja sangat ideal, walaupun belum tentu mustahil diwujudkan. Berkaca dari hasil Pemilu selama ini, untuk mencapai angka kritis 30% yang dianjurkan saja perjuangan menuju ke arah yang diharapkan itu memerlukan energi luar biasa untuk pengawalan tak kenal lelah dari banyak pihak, tak terkecuali gerakan perempuan.
Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah minimum 30% (merupakan suatu critical mass untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Penetapan jumlah 30% ditujukan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Perlakuan khusus berlaku bagi warga negara yang telah mengalami ketidaksetaraan (diskriminasi), baik dalam peluang, akses dan dampak. Dalam dunia politik, perempuan adalah bagian dari warga negara yang selama ini mengalami diskriminasi sehingga untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dibutuhkan perlakuan khusus atau kebijakan affirmasi.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) mengamanatkan Negara untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, di antaranya dengan tindakan affirmasi (affirmative action). Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ini bukanlah pengistimewaan bagi perempuan, melainkan bentuk koreksi dan kebijakan affirmasi 30% adalah minimum atau sekurang-kurangnya atau paling sedikit, bukan“jatah” yang dimaknai tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditentukan. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen sama sekali tidak ditujukan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Ketentuan ini justru merupakan tindakan khusus sementara (temporary special measure) agar hak-hak perempuan yang selama ini didiskriminasi oleh nilainilai budaya yang dikonstruksi dalam masyarakat dapat ditegakkan.
Pemilihan Umum, yang menetapkan kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan dari partai-partai politik, Komite prihatin karena undang-undang tersebut tidak menentukan sanksi atau mekanisme penegakan guna memastikan dipatuhinya kuota tersebut. Kuota 30% ini memang pada akhirnya merupakan sebuah affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan publik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan ketidakseimbangan dalam representasi politik.
Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%).
Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.
Berkaca dari pengalaman Pemilu 2004 itulah kemudian diterapkan zipper system pada UU Pemilu 2008 dengan mengharuskan Parpol menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diantara tiga caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan perempuan masuk ke dalam parlemen karena selalu ditempatkan di nomor urut besar dan tidak menjadi calon parpol yang diprioritaskan. Meskipun sudah diterapkan zipper system 1:3 di dalam Pemilu 2008, tetapi masih terdapat beberapa Parpol yang akhirnya menempatkan caleg perempuan hanya pada angka terbawah dalam kelipatan 3 yakni untuk nomor urut 3, 6 dan 9. Namun demikian, jika tujuan dilakukannya zipper system ini berhasil, maka sekurang-kurangnya terdapat satu perempuan dari tiga anggota legislatif yang terpilih di dalamlegislatif.
Penjelasan tersebut telah menggambarkan bagaimana zipper system menjadi upaya penting untuk mendorong keterwakilan perempuan di tubuh parlemen. Perlu menjadi catatan penting, bahwa zipper system ini hanya dapat berlaku apabila disandingkan dengan sistem nomor urut, seperti yang diterapkan pada Pemilu 2004. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan, ketika terjadi perubahan aturan main di dalam sistem Pemilu. Empat bulan menjelang Pemilu, aktivis perempuan dikejutkan dengan hasil Judicial Review atas UU No.10 Tahun 2008 Pasal 214 yang menetapkan suara terbanyak sebagaimekanisme pengganti aturan nomor urut dalam penentuan caleg menjadi anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil Judicial Review ini, karena Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 dinilai bertentangan dengan Pasal 1ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Perubahan bunyi pasal dari digunakannya aturan nomor urut menjadi aturan suaraterbanyak merupakan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemilu yang ada di dalam UU,khususnya terhadap tindakan afirmasi yang dilakukan untuk mendongkrak keterwakilan perempuan di DPR/DPRD. Dengan dihapuskannya aturan nomor urut oleh Judicial Review UU Pemilu, maka affirmative action yang diatur oleh Pasal 55 ayat 2 tersebut menjadi tidak ada artinya. Tidak berlakunya zipper system, berarti tidak berlakunya affirmative action, dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan diparlemen.
Dalam Pemilu 2009, upaya affirmative action dilakukan dengan mengelaborasikan sistem kuota, zipper system dan aturan nomor urut. Elaborasi tindakan afirmasi ini merupakan hasil pembelajaran terhadap apa yang terjadi di dalam Pemilu 2004. Sesuai dengan UU Pemilu yang berlaku pada Pemilu 2004 (UU Pemilu No.12 tahun 2003), maka caleg terpilih ditetapkan berdasarkan aturan nomor urut. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa caleg dengan nomor urut kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk menjadi anggota legislatif.
[1] Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 474.
[2] Afan Gafar, “Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 251.
[3] Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, “Panduan Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan”, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 5.
[4] Ibid.
[5] “Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Perbandingan Perempuan dan Laki-Laki” dalam http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/juli/statistik_dpr_09-14-jenis_kelamin.pdf diakses tanggal 3 Juni 2012
[6] “Kuota Perempuan Tantangan bagi Parpol” dalam http://www.mediaindonesia.com/data/pdf/pagi/2008-09/2008-09-02_02.pdf diakses tanggal 6 Juni 2012
[7] “Hasil Sensus Penduduk 2010” dalam http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?sp=0, diakses tanggal 6 Juni 2012








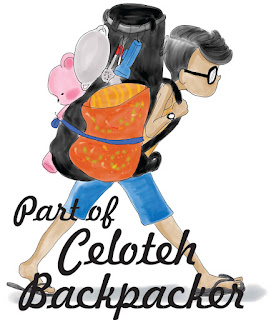


0 Comments